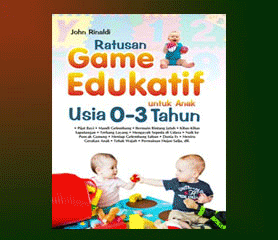Bulan ini kita telah memasuki dalam
bulan Rajab. Tidak sedikit kaum Muslimin di Indonesia, yang
mentradisikan puasa Sunnah ketika memasuki bulan-bulan mulia seperti
bulan Rajab. Persoalannya, setelah merebaknya aliran Salafi-Wahabi di
Indonesia, beragam tradisi ibadah dan keagamaan yang telah berlangsung
sejak masuknya Islam ke Nusantara, seperti puasa Sunnah di bulan Rajab
selalu dipersoalkan oleh mereka dengan alasan bid’ah, haditsnya palsu
dan alasan-alasan lainnya. Seakan-akan mereka ingin menghalangi umat
Islam dari mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan beribadah puasa.
Oleh karena itu tulisan ini, berupaya menjernihkan hukum puasa Rajab
berdasarkan pandangan para ulama yang otoritatif.
Hukum Puasa Rajab
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa Rajab.
Pertama, mayoritas ulama dari
kalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa puasa
Rajab hukumnya Sunnah selama 30 hari. Pendapat ini juga menjadi qaul
dalam madzhab Hanbali.
Kedua, para ulama madzhab
Hanbali berpendapat bahwa berpuasa Rajab secara penuh (30 hari) hukumnya
makruh apabila tidak disertai dengan puasa pada bulan-bulan yang
lainnya. Kemakruhan ini akan menjadi hilang apabila tidak berpuasa dalam
satu atau dua hari dalam bulan Rajab tersebut, atau dengan berpuasa
pada bulan yang lain. Para ulama madzhab Hanbali juga berbeda pendapat
tentang menentukan bulan-bulan haram dengan puasa. Mayoritas mereka
menghukumi sunnah, sementara sebagian lainnya tidak menjelaskan
kesunnahannya.
Berikut pernyataan para ulama madzhab empat tentang puasa Rajab.
Madzhab Hanafi
Dalam al-Fatawa al-Hindiyyah (1/202) disebutkan:
في الفتاوي الهندية 1/202 : ( المرغوبات من الصيام أنواع ) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان وصوم عاشوراء ) اه
“Macam-macam puasa yang disunnahkan
adalah banyak macamnya. Pertama, puasa bulan Muharram, kedua puasa bulan
Rajab, ketiga, puasa bulan Sya’ban dan hari Asyura.”
Madzhab Maliki
Dalam kitab Syarh al-Kharsyi ‘ala Mukhtashar Khalil (2/241), ketika menjelaskan puasa yang disunnahkan, al-Kharsyi berkata:
(والمحرم ورجب وشعبان ) يعني
: أنه يستحب صوم شهر المحرم وهو أول الشهور الحرم , ورجب وهو الشهر الفرد
عن الأشهر الحرم ) اه وفي الحاشية عليه : ( قوله : ورجب ) , بل يندب صوم
بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة فالحجة ) اه
“Muharram, Rajab dan Sya’ban. Yakni,
disunnahkan berpuasa pada bulan Muharram – bulan haram pertama -, dan
Rajab – bulan haram yang menyendiri.” Dalam catatan pinggirnya: “Maksud
perkataan pengaram, bulan Rajab, bahkan disunnahkan berpuasa pada semua
bulan-bulan haram yang empat, yang paling utama bulan Muharram, lalu
Rajab, lalu Dzul Qa’dah, lalu Dzul Hijjah.”
Pernyataan serupa bisa dilihat pula dalam kitab al-Fawakih al-Dawani (2/272), Kifayah al-Thalib al-Rabbani (2/407), Syarh al-Dardir ‘ala Khalil (1/513) dan al-Taj wa al-Iklil (3/220).
Madzhab Syafi’i
Imam al-Nawawi berkata dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (6/439),
قال الإمام
النووي في المجموع 6/439 : ( قال أصحابنا : ومن الصوم المستحب صوم الأشهر
الحرم , وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب , وأفضلها المحرم , قال
الروياني في البحر : أفضلها رجب , وهذا غلط ; لحديث أبي هريرة الذي سنذكره
إن شاء الله تعالى { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ) اه
“Teman-teman kami (para ulama
madzhab Syafi’i) berkata: “Di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa
bulan-bulan haram, yaitu Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab,
dan yang paling utama adalah Muharram. Al-Ruyani berkata dalam al-Bahr:
“Yang paling utama adalah bulan Rajab”. Pendapat al-Ruyani ini keliru,
karena hadits Abu Hurairah yang akan kami sebutkan berikut ini insya
Allah (“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa bulan
Muharram.”)”.
Pernyataan serupa dapat dilihat pula dalam Asna al-Mathalib (1/433), Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah (2/53), Mughni al-Muhtaj (2/187), Nihayah al-Muhtaj (3/211) dan lain-lain.
Madzhab Hanbali
Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata dalam kitab al-Mughni (3/53):
قال ابن قدامة في المغني 3/53 فصل : ويكره إفراد رجب بالصوم . قال أحمد : وإن
صامه رجل , أفطر فيه يوما أو أياما , بقدر ما لا يصومه كله … قال أحمد :
من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه ولا يشبهه
برمضان ) اه
“Pasal. Dimakruhkan mengkhususkan
bulan Rajab dengan ibadah puasa. Ahmad bin Hanbal berkata: “Apabila
seseorang berpuasa Rajab, maka berbukalah dalam satu hari atau beberapa
hari, sekiranya tidak berpuasa penuh satu bulan.” Ahmad bin Hanbal juga
berkata: “Orang yang berpuasa satu tahun penuh, maka berpuasalah pula di
bulan Rajab. Kalau tidak berpuasa penuh, maka janganlah berpuasa Rajab
terus menerus, ia berbuka di dalamnya dan jangan menyerupakannya dengan
bulan Ramadhan.”
Ibnu Muflih berkata dalam kitab al-Furu’ (3/118):
وفي الفروع لابن مفلح 3/118 : ( فصل : يكره إفراد رجب بالصوم نقل
حنبل : يكره , ورواه عن عمر وابنه وأبي بكرة , قال أحمد : يروى فيه عن عمر
أنه كان يضرب على صومه , وابن عباس قال : يصومه إلا يوما أو أياما … وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة , قال صاحب المحرر : وإن لم يله .
“Pasal. Dimakruhkan mengkhususkan
bulan Rajab dengan berpuasa. Hanbal mengutip: “Makruh, dan meriwayatkan
dari Umar, Ibnu Umar dan Abu Bakrah.” Ahmad berkata: “Memuku seseorang
karena berpuasa Rajab”. Ibnu Abbas berkata: “Sunnah berpuasa Rajab,
kecuali satu hari atau beberapa hari yang tidak berpuasa.” Kemakruhan
puasa Rajab bisa hilang dengan berbuka (satu hari atau beberapa hari),
atau dengan berpuasa pada bulan yang lain dalam tahun yang sama.
Pengarang al-Muharrar berkata: “Meskipun bulan tersebut tidak
bergandengan.”
DALIL PUASA RAJAB
Dalil Mayoritas Ulama
Mayoritas ulama yang berpandangan bahwa
puasa Rajab hukumnya sunnah sebulan penuh, berdalil dengan beberapa
banyak hadits dan atsar. Dalil-dalil tersebut dapat diklasifikasi
menjadi tiga:
Pertama, hadits-hadits yang
menjelaskan keutamaan puasa sunnah secara mutlak. Dalam konteks ini,
al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata dalam al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah (2/53) dan fatwa beliau mengutip dari fatwa al-Imam Izzuddin bin Abdussalam (hal. 119):
قال ابن حجر كما في الفتاوى الفقهية الكبرى 2/53
ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من
منع صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه :نذر
صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ
أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم
يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى
لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم مثل : قوله
صلى الله عليه وسلم { يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم } وقوله صلى
الله عليه وسلم { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } وقوله { إن أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما } وكان داود يصوم من غير تقييد بما عدا رجبا من الشهور ) اه
“Ibnu Hajar, (dan sebelumnya Imam
Izzuddin bin Abdissalam ditanya pula), tentang riwayat dari sebagian
ahli hadits yang melarang puasa Rajab dan mengagungkan kemuliaannya, dan
apakah berpuasa satu bulan penuh di bulan Rajab sah? Beliau berkata
dalam jawabannya: “Nadzar puasa Rajab hukumnya sah dan wajib, dan dapat
mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukannya. Orang yang melarang
puasa Rajab adalah orang bodoh dengan pengambilan hukum-hukum syara’.
Bagaimana mungkin puasa Rajab dilarang, sedangkan para ulama yang
membukukan syariat, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan
masuknya bulan Rajab dalam bulan yang makruh dipuasai. Bahkan berpuasa
Rajab termasuk qurbah (ibadah sunnah yang dapat mendekatkan) kepada
Allah, karena apa yang datang dalam hadits-hadits shahih yang
menganjurkan berpuasa seperti sabda Nabi SAW: “Allah berfirman, semua
amal ibadah anak Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa”, dan sabda
Nabi SAW: “Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum
menurut Allah dari pada minyak kasturi”, dan sabda Nabi SAW:
“Sesungguhnya puasa yang paling utama adalah puasa saudaraku Dawud. Ia
berpuasa sehari dan berbuka sehari.” Nabi Dawud AS berpuasa tanpa
dibatasi oleh bulan misalnya selain bula Rajab.”
Al-Syaukani berkata dalam Nail al-Authar (4/291):
وقال
الشوكاني في نيل الأوطار 4/291 : ( وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على
العموم والخصوص : أما العموم : فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر
الحرم وهو منها بالإجماع . وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم …
) اه
“Telah datang dalil yang menunjukkan
pada disyariatkannya puasa Rajab, secara umum dan khusus. Adapun hadits
yang bersifat umum, adalah hadits-hadits yang datang menganjurkan puasa
pada bulan-bulan haram. Sedangkan Rajab termasuk bulan haram
berdasarkan ijma’ ulama. Demikian pula hadits-hadits yang datang tentang
disyariatkannya puasa sunnat secara mutlak.”
Kedua, hadits-hadits yang
menganjurkan puasa bulan-bulan haram, antara lain hadits Mujibah
al-Bahiliyah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam al-Sunan (2/322) sebagai berikut ini:
عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه : أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته
وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي
جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا
بليل منذ فارقتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم عذبت نفسك ثم قال صم
شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال
صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من
الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها )
Dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayah
atau pamannya, bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW kemudian pergi. Lalu
datang lagi pada tahun berikutnya, sedangkan kondisi fisiknya telah
berubah. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku?”
Beliau bertanya: “Kamu siapa?” Ia menjawab: “Aku dari suku Bahili, yang
datang tahun sebelumnya.” Nabi SAW bertanya: “Kondisi fisik mu kok
berubah, dulu fisikmu bagus sekali?” Ia menjawab: “Aku tidak makan
kecuali malam hari sejak meninggalkanmu.” Lalu Rasulullah SAW bersabda:
“Mengapa kamu menyiksa diri?” Lalu berliau bersabda: “Berpuasalah di
bulan Ramadhan dan satu hari dalam setiap bulan.” Ia menjawab:
“Tambahlah kepadaku, karena aku masih mampu.” Beliau menjawab:
“Berpuasalah dua hari dalam sebulan.” Ia berkata: “Tambahlah, aku masih
kuat.” Nabi SAW menjawab: “Berpuasalah tiga hari dalam sebulan.” Ia
berkata: “Tambahlah.” Nabi SAW menjawab: “Berpuasalah di bulan haram dan
tinggalkanlah, berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah,
berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu
Majah).
Mengomentari hadits tersebut, Imam al-Nawawi berkata dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab
(6/439): “Nabi SAW menyuruh laki-laki tersebut berpuasa sebagian dalam
bulan-bulan haram tersebut dan meninggalkan puasa di sebagian yang lain,
karena berpuasa bagi laki-laki Bahili tersebut memberatkan fisiknya.
Adapuan bagi orang yang tidak memberatkan, maka berpuasa satu bulan
penuh di bulan-bulan haram adalah keutamaan.” Komentar yang sama juga
dikemukakan oleh Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari dalam Asna al-Mathalib (1/433) dan Ibnu Hajar al-Haitami dalam Fatawa-nya (2/53).
Ketiga, hadits-hadits yang
menjelaskan keutamaan bulan Rajab secara khusus. Hadits-hadits tersebut
meskipun derajatnya dha’if, akan tetapi masih diamalkan dalam bab
fadhail al-a’mal, seperti ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam Fatawa-nya (2/53).
Di antara hadits yang menjelaskan keutamaan puasa Rajab secara khusus adalah hadits Usamah bin Zaid berikut ini:
في سنن النسائي 4/201 : ( عن أسامة بن زيد قال قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ) اه
“Dalam Sunan al-Nasa’i (4/201): Dari
Usamah bin Zaid, berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu
berpuasa dalam bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan
Sya’ban?” Beliau menjawab: “Bulan Sya’ban itu bulan yang dilupakan oleh
manusia antara Rajab dan Ramadhan.”
Mengomentari hadits tersebut, Imam al-Syaukani berkata dalam kitabnya Nail al-Authar
(4/291): “Hadits Usamah di atas, jelasnya menunjukkan disunnahkannya
puasa Rajab. Karena yang tampak dari hadits tersebut, kaum Muslimin pada
masa Nabi SAW melalaikan untuk mengagungkan bulan Sya’ban dengan
berpuasa, sebagaimana mereka mengagungkan Ramadhan dan Rajab dengan
berpuasa.”
Keempat, atsar dari ulama salaf
yang saleh. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa beberapa
ulama salaf yang saleh menunaikan ibadah puasa Rajab, seperti Hasan
al-Bashri, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dalam
kitab-kitab hadits seperti Mushannaf Ibn Abi Syaibah dan lain-lain.
Dalil Madzhab Hanbali
Sebagaimana dimaklumi, madzhab Hanbali
berpendapat bahwa mengkhususkan puasa Rajab secara penuh dengan ibadah
puasa adalah makruh. Akan tetapi kemakruhan puasa Rajab ini bisa hilang
dengan dua cara, pertama, meninggalkan sehari atau lebih dalam bulan
Rajab tanpa puasa. Dan kedua, berpuasa di bulan-bulan di luar Rajab,
walaupun bulan tersebut tidak berdampingan dengan bulan Rajab.
Para ulama yang bermadzhab Hanbali,
memakruhkan berpuasa Rajab secara penuh dan secara khusus, didasarkan
pada beberapa hadits, antara lain:
Hadits dari Zaid bin Aslam, bahwa
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Rajab, lalu beliau menjawab:
“Di mana kalian dari bulan Sya’ban?” (HR. Ibnu Abi Syaibah [2/513] dan
Abdurrazzaq [4/292]. Tetapi hadits ini mursal, alias dha’if).
Hadits Usamah bin Zaid. Ia selalu
berpuasa di bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya:
“Berpuasalah di bulan Syawal.” Lalu Usamah meninggalkan puasa di
bulan-bulan haram, dan hanya berpuasa di bulan Syawal sampai meninggal
dunia.” (HR. Ibn Majah [1/555], tetapi hadits ini dha’if. Hadits ini
juga dinilai dha’if oleh Syaikh al-Albani.).
Hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW
melarang puasa Rajab. (HR. Ibn Majah [1/554], tetapi hadits ini dinilai
dha’if oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa al-Kubra [2/479], dan lain-lain).
Madzhab Hanbali juga berdalil dengan
beberapa atsar dari sebagian sahabat, seperti atsar bahwa Umar pernah
memukul orang karena berpuasa Rajab, atsar dari Anas bin Malik dan
lain-lain. Tetapi atsar ini masih ditentang dengan atsar-atsar lain dari
para sahabat yang justru melakukan puasa Rajab. Disamping itu,
dalil-dalil para ulama yang menganjurkan puasa Rajab jauh lebih kuat dan
lebih shahih sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Demikian catatan sederhana tentang hukum puasa Rajab. Wallahul muwaffiq.
Muhammad Idrus Ramli